
Pernahkah kalian melihat mata anak yang berbinar saat asyik mengetik di layar? Atau mendengar tawa tiba-tiba mereka yang seolah punya tembarungan rahasia? Di era chatbot yang bisa jadi ‘teman bicara’ pertama, perasaan bercampur-baur: haru dengan kemajuan teknologi, tapi juga sedih dengan jarak yang mungkin terbentuk. Kita sebagai orangtua sering terjebak di antara dua dunia ini. Tapi, bagaimana jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda? Teknologi bukan musuh, tapi cermin dari kebutuhan batin mereka yang ingin didengar. Biar ayah cerita sedikit pengalamannya ya…
Mengapa AI Menjadi Teman Curhat Utama

Nah, ngomong-ngomong teknologi, anak-anak hari ini menemukan zona nyaman di chatbot karena tanpa penilaian. Tapi, pernahkah kita berpikir lebih jauh? Mungkin alasan remaja lebih sering curhat ke AI daripada ke orangtua bukan karena mereka tak butuh kita. Hmm, tapi mungkin lebih karena mereka butuh ruang tanpa takut dicecar atau dihakimi. Sebenarnya, ayah juga pernah bingung, kok bisa anak-anak jadi comfortable bahas perasaan sama AI daripada sama ayahnya sendiri? ‘Khawatir anak kecanduan chatting sama AI? ChatGPT sekarang kasih peringatan lho!’ Ini bukan tanda kelemahan, tapi tantangan kita sebagai orangtua untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Daripada langsung memberi ‘peraturan’, mungkin lebih baik kita mulai dengan pertanyaan sederhana: ‘Cerita apa yang bikin kamu tertawa tadi?’ Dengan nada penasaran, bukan interogasi. Ini ayah belajar sendiri, dari pengalaman melihat istri yang selalu sabar saat anak-anak curhat meski sudah capek seharian.
Membangun Jembatan Emosi: Bukan Larang, tapi Belajar Bersama

Teknologi itu seperti aliran sungai yang deras. Daripada membendungnya, lebih baik kita ajar anak berenang. ‘Dampingi anak pakai AI tuh kayak ngajarin berenang: jangan dilarang, tapi diawasi arusnya’ Data menunjukkan, anak yang dibimbing orangtua saat teknologinya justru percaya lebih ke orangtuanya. Ini yang ayah coba terapkan. Setelah anak berinteraksi dengan chatbot, kita bisa sambil menyeka makan malam tanyakan, ‘Kalau jawabannya kurang pas, kamu gimana nanti?’ Pelajari bersama, jadi justru pertemuan ibu-bapak dan jadi aktivitas bonding. Anak dan ayah suka nonton video tutorial ngoding setiap Sabtu pagi, lalu diskusi apa yang dipelajari. ‘Waduh, bahkan perusahaan AI besar pun khawatir anak muda terlalu tergantung buat putusin masalah!’ Tapi kenyataannya, saat kita hadir di samping ekplorasi digital mereka, kita juga belajar lebih banyak tentang dunia anak-anak kita. Seperti saat anak bertanya, “Ayah, ini algoritma kerja gimana ya?” Ayah senang bisa berbagi pengeteruan dengan cara yang mudah dipahami.
Begitulah pelabuhan digital dimulai dari percaya satu sama lain. Ayah ingat saat pertama kali anak meminta tolong buka aplikasi bahasa baru di ponsel. Daripada langsung kasih password, kata ayah, “Biarkan ayah pelajari bareng kamu, jadi kita bisa ngobrolin keamanannya juga.” On, anak senang sekali bisa ajak ayah belajar hal baru. Itulah saatnya saya sadar, teknologi bisa jadi jembatan bukan tembok. Ketika istri sedang sibuk, anak saya justru berbagi tentang teman di sekolahnya dengan lebih lengkap saat ayah sedang mengerjakan proyek kecil di laptop. Seperti layaknya peta navigasi, teknologi membantu menemukan jalan, tapi orangtua lah yang memastikan arahnya benar.
Keamanan Digital: Talk Less, Listen More

Pernah merasa ‘Jangan sampai rahasia keluarga dibocorin ke ChatGPT! Anak perlu diajarin digital safety’? Ayah pernah begitu. Tapi kemudian sadar, daftar larangan yang panjang itu bagaikan pagar yang semakin membuat anak penasaran. Daripatu aturan panjang, yuk buat kesepakatan bareng-bareng. Misal, ‘Ayo kita cari aplikasi yang aman sama-sama’ atau ‘Kalau ada yang bikin tidak nyaman kamu, segera bilang ya ayah.’ Teknologi keamanan penting, tapi kepercayaan adalah fondasinya. Bagai pelabuhan yang dibangun di pasir, keamanan digital butuh fondasi percaya yang kuat. Seperti kapal yang membutuhkan pelabuhan, anak juga membutuhkan orang tua sebagai tempat berlabuh aman.
Dari pengalaman ayah, anak akan membagikan rahasia mereka pada orang yang paling mereka percaya, bukan pada alat terbaik ketika ada kehadiran yang nyata. Ayah ingat, kalau istri lagi sibuk kerja, anaknya sering cerita pengalaman sekolah ke ayah sebelum beres mengerjakan PR dulu. Ini bukan mengganti kita orang tua, tapi bukti bahwa masih butuh pendengar nyata, meski teknologi sudah maju. Just like how my daughter shows me her new drawing after she’s been using an AI art generator. She’s excited to share her creation with a real person who understands her emotions.
Sentuhan Manusia: Kuncinya Tergantikan
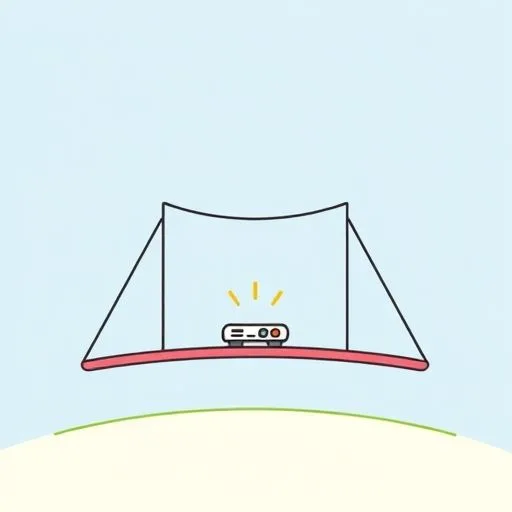
‘Anak-anak bisa jatuh cinta sama AI? Hati-hati bahayanya, parents!’ Pertanyaan yang sering kami diskusi saat anak sudah tidur. Di balik semua kecanggihan teknologi, ada satu kebenaran sederhana: sentuhan manusia takkan tergantikan. Saat anak sedih karena jawaban AI yang berputar-putar, pelukan kita yang terasa paling nyaman. ‘Jangan asal percaya jawaban AI, nanti kasih nasihat sesat bahaya banget!’ Ini peringatan penting bagi kita semua. Teknologi akan terus berkembang, tapi peran kita sebagai orang tua tidak pernah berubah: menjadi pelabuhan pertama saat badai menerjang.
Saat anak sedih karena jawaban AI yang berputar-putar, pelukan kita yang terasa paling nyaman. ‘Jangan asal percaya jawaban AI, nanti kasih nasihat sesat bahaya banget!’ Ini peringatan penting bagi kita semua. Teknologi akan terus berkembang, tapi peran kita tidak pernah berubah: menjadi pelabuhan pertama saat badai menerjang.
Kalau AI sudah kaya teman sekamar anak, kapan kita bisa masuk jadi ‘pelabuhan utamanya’? Jawabannya mungkin sederhana: dengan kehadiran yang konsisten, dengaran yang penuh perhatian, dan terus belajar memahami dunia mereka meski berbeda generasi. Begitulah ayah mencoba menjadi ayah zaman now. Seperti saat anak mengaku takut tidur sendiri karena cerita horor di aplikasi chat, Ayah langsung aja diajak ngobrol lebih lama malam itu. Meski capek setelah kerja, kehadiran itu yang jadi pelabuhan diamannya.
Source: Lawmakers Want To Shield Kids From AI Chatbots. But Restricting Them Could Cut Off a Mental Health Lifeline., Reason, 12 September 2025
