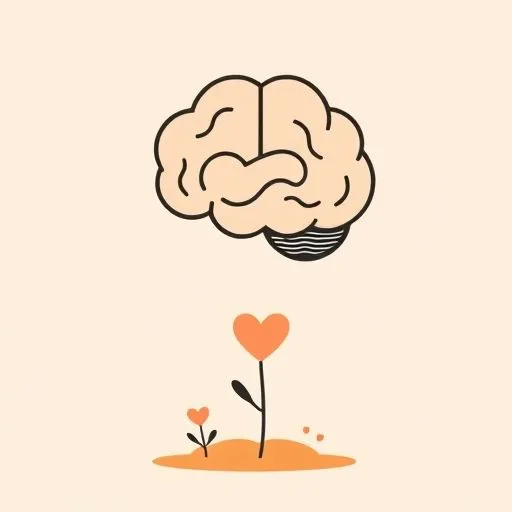
Ah, pagi ini hujan gerimis turun lembut sambil saya mengantar Nisa ke SD—jaraknya cuma sebentar jalan kaki dari rumah. Sepanjang jalan, saya terus berpikir tentang obrolan semalam dengan tetangga soal gengsi anak muda sekarang. Katanya, banyak sarjana bergelar cum laude malah jadi tukang ojek online karena susah cari kerja. Tiba-tiba, berita tentang Sam Altman CEO OpenAI menyebut profesi kesehatan justru “tahan robot” membuat hati ini berdebar-debar. Apa artinya ini bagi kita yang khawatir anak kita nanti terlindas gelombang AI? Percayalah, sahabat, ada pelabuhan tenang di tengah badai ini—dan kita akan jelajahi bersama!
Gelombang Kecemasan: “Robot Apa Lagi yang Akan Ambil Pekerjaan Anakku?”
Sudah jadi obrolan warung kopi tiap minggu: teman-teman di sini gelisah melihat anak kelas 12 SMP yang mulai bertanya, “Bapak, jurusan apa yang aman dari AI nanti?” Ingat waktu kita kecil, dulu jadi guru atau akuntan dianggap “karier bergengsi”? Sekarang malah jadi daftar teratas yang disebut riset Mckinsey bisa terotomatisasi hingga 70%! Bahkan coding pun kini diuji oleh GitHub Copilot.
Waktu Nisa pulang bawa PR tentang robot di sekolah, saya sempat jantungan: “Jangan-jangan nanti anak kita hidup seperti di film Terminator, Bapak?” Astaga, sampai mimpi buruk saya! Dalam keresahan itu, saya teringat momen hangat di puskesmas kemarin… Saat istri kontrol ke puskesmas, ada cahaya kecil yang menghangatkan. Si bidan tersenyum lembut sambil mengusap kening istri: “Kita manusia, Bu, butuh sentuhan hangat—bukan mesin dingin.” Ucapannya tiba-tiba jadi petir di siang bolong: apakah ini jawaban atas kecemasan kita?
“Teknologi bisa ubah banyak hal—tapi rapport pasien dan perawat? Itu tetap jantung manusia.”
Lihat data OpenAI: healthcare justru “satu-satunya sektor yang terus tumbuh” di tengah gempa AI! Kenapa? Karena di balik rumah sakit dan klinik, ada hal yang gak bisa diklik—gotong royong kemanusiaan yang AI mustahil tiru. Saat nenek saya sakit tahun lalu, yang membuat semangatnya bangkit bukan obat mahal tapi tangan perawat muda yang genggam tangannya sambil bilang, “Mari kita lawan bersama!”.
Mengapa Perawat di Indonesia Takkan Digantikan Robot? Ini Bukan Sekadar Nasib Baik!
Sebenarnya, ini bukan kebetulan. Coba kita hitung dengan kepala dingin seperti cara mengatur jadwal sekolah Nisa. Riset McKinsey bilang hanya 35% tugas di bidang kesehatan yang hanya 35% tugas di bidang kesehatan yang bisa diotomatisasi—bandingkan dengan sektor legal (90%) atau administrasi (80%)! Kenapa?
Pikirkan seperti ini: saat Nisa demam 40 derajat, saya bisa telemedicine via aplikasi tapi yang membuat hati tenang justru perawat di Puskesmas dekat pasar yang ngemil kerupuk dan bilang, “Paniknya kayak cabe rawit! Ayo kita kompres pelan-pelan.” Itulah nilai yang tak bisa dihitung algoritma: kemampuan membaca raut wajah, kepekaan bahasa tubuh, dan naluri kemanusiaan.
Saat pasien tua di desa takut disuntik, perawat justru main tebak-tebakan lewat cerita. Taktik yang lahir dari pengalaman hidup, bukan machine learning. Bahkan di desa, tradisi “zaitun” (salah ucap dari Arab “zaytun” yang maksudnya kebaikan) ini adalah SPBU-nya hubungan pasien dan tenaga kesehatan. Saat bidan desa datang ke rumah bawa obat juga kalehan lebaran, kita benar-benar merasakan bahwa hati itu tak bisa dibuat robot!
Aksi Nyata: Tanamkan “Benih Humanity” pada Anak Sejak Dini!
- Latih Empati lewat Permainan: Saat Nisa main dokter-dokteran, saya minta ia “periksa perasaan” bonekanya. “Bagaimana carinya kita bikin boneka ini percaya?” Ini latihan natural untuk mengasah kecerdasan emosional—kunci jadi tenaga kesehatan yang memberi “ruh”.
- Kenalkan Dunia Nyata: Setiap bulan, kami sengaja mampir ke posyandu RW biar Nisa lihat langsung ibu-ibu berangsur nasi bungkus untuk lansia yang periksa gratis. Ia belajar kesehatan itu tak lepas dari solidaritas sosial—prinsip mustahil di-download ke AI.
- Berani Bicara tentang Kegagalan: Pekan lalu, Nisa nangis karena salah menyiram tanaman di sekolah. Saya bilang: “Di kesehatan, kesalahan kecil bisa membuat nyawa terancam. Makanya, kita perlu kejujuran dan keberanian mengakui kesalahan.” Ini fondasi integritas yang justru diapresiasi di era AI. Seperti pohon—budi itu akar yang buat kita tahan badai.
Pelabuhan Tenang di Tengah Badai: Pesan untuk Para Sahabat Orang Tua
Pagi ini, Nisa pulang sambil larilah pantatnya, “Clip-clop” tasnya. Ia bilang, “Pak, Bu Guru ajari kita harus jadi manusia yang bermanfaat!”
Saya langsung berdoa dalam hati: Ya Allah, semoga ia selalu ingat mesin pintar bisa periksa rontgen, tapi hati manusia tetap penyembuh terbaik. Kadang saya bertanya, ‘Cukupkah usaha kecil ini?’ lalu tersadar bahwa setiap langkah kita berarti. Di tengah fenomena AI ini, kita perlu tingkatkan mutu ‘jantung’ anak kita. Mereka harus memiliki spirit ‘gotong-royong’, naluri membaca isyarat rasa sakit, dan keberanian menawarkan sentuhan bukan sekadar instruksi.
Rocket science? Gak juga. Kita bisa mulai dari metik daun kelor bersama Nisa untuk neneknya, latih anak membaca ekspresi teman saat main bola, atau biarkan ia ringkas abis komputer agak kepenuhan masalah. Dengan menekankan hal-hal “non-digital”, seperti kata Sam Altman, kita sudah men-tanam AI-proof skill yang nilai ekonominya akan meningkat drastis di 2030 sana.
Sumber: Strategi Tahan Badai AI Versi OpenAI CEO, Fortune, 2025-09-11
