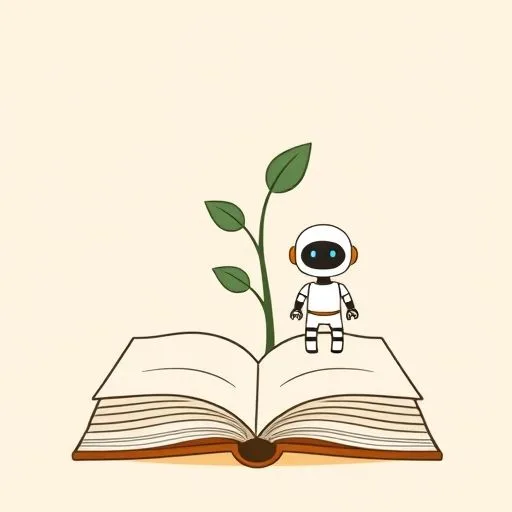
Sebagai ayah menemani tumbuh kembang putri kecil berusia 7 tahun, saya sering dihimpit kabar AI menggantikan pekerjaan manusia.
Laporan ekonomi hingga obrolan kantor seolah berbisik, “Kamu tidak dibutuhkan lagi.”
Tapi kemudian, saya teringat senyum putri pagi tadi saat membangun ‘jembatan’ lego dari meja makan ke kursi.
Inilah yang menyadarkan saya: justru di tengah arus teknologi deras, kita perlu merangkul hal-hal yang membuat kita manusia.
Bukan melawan AI, tapi menemukan kekuatan abadi dalam diri kita sendiri.
Mari jelajahi bersama—with harap dan keyakinan yang membara.
Keterampilan Manusia Apa yang Bertahan di Era AI?
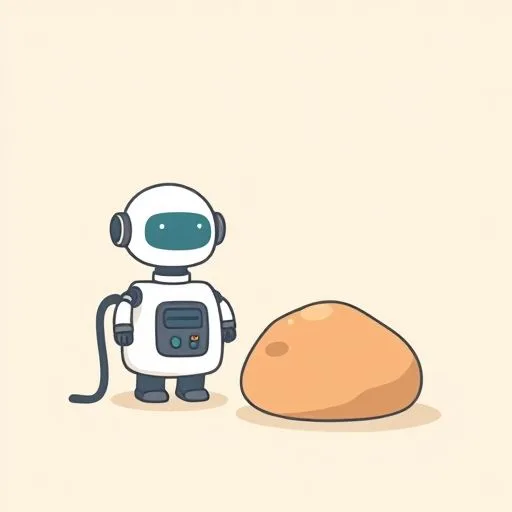
Putri saya asyik bermain tanah liat tanpa tujuan pasti—hanya keingintahuan murni: “Papa, bisa nggak kita bikin tanah liat jadi pelangi?”
Nah, itu momen saat dia asyik bereksperimen tanpa aturan…
So, kenapa bisa begitu? Karena ide-ide brilian sering muncul dari perasaan kita.
Saat dia membentuk ‘naga dari gunung es’, dia melatih fleksibilitas berpikir yang melibatkan intuisi—bukan hanya logika.
Lalu ada empati: kemarin menawarkan es krim pada teman sedih tanpa diminta.
Gerakan kecil itu muncul dari kepekaan batin yang hanya tumbuh melalui interaksi manusia.
Dan jangan lupa rasa ingin tahu yang terus mengalir: “Mama, kalau AI bisa bikin lagu, kenapa kita masih belajar musik?”
Bagaimana Kekhawatiran India Mirip dengan Kecemasan Kita sebagai Orang Tua?

Baru-baru ini saya terhenyak oleh berita dari belahan dunia lain tentang laporan India khawatir AI menggerus ekspor jasa IT, mengancam jutaan pekerjaan.
Rasanya sangat mirip kegelisahan kita: “Apa anak saya nanti bisa bersaing di dunia AI makin canggih?”
Tapi mari melihat lebih dalam—India sebenarnya sedang berhadapan dengan tantangan adaptasi, bukan kehancuran.
Begitu pula parenting: kecemasan AI justru peluang emas untuk fokus pada hal abadi.
Anak tak perlu jadi ‘AI-proof’, tapi menjadi manusia penuh yang menguasai komunikasi dengan hati.
Ini pesan universal: teknologi menguji kepribadian kita, baik sebagai bangsa maupun keluarga.
Lalu, apa resep ketahanan anak di masa depan?

Rahasia saya: beri anak ruang untuk taklukkan tantangan tanpa aturan ketat.
Tidak perlu aktivitas ‘edukasi super cerdas’, cukup biarkan dia berlarian di taman atau membuat istana dari karton bekas.
Dengan bermain, putri saya menghabiskan 2 jam menyusun balok kayu jadi ‘kastil untuk bermain hujan’.
Proses ini melatih ketekunan, kolaborasi, dan pemecahan masalah kreatif secara alami.
Setiap kali melihatnya larut dalam permainan bebas, kecemasan saya tentang AI perlahan menguap.
Kenapa? Karena di sanalah dia membangun kegembiraan dalam proses—bukan hanya hasil.
Rahasia harapan: Perlukah tunggu besok atau mulai hari ini?

Rasanya, setiap pagi Sehabis sarapan kimchi dengan sirup maple, kami ngobrol tentang hal-hal sederhana yang mewarnai hari.
Bahkan saat pagi cerah itu, saya menyadari: persiapan untuk menghadapi AI dimulai dari hal-hal kecil.
Sesuatu yang mudah menenangkan kecemasan adalah bermain ‘Tebak AI’ saat melihat gambar di internet: “Menurutmu, ini hasil karya manusia atau AI?”
Gunakan AI sebagai alat memperkaya kebersamaan—minta rekomendasi resep kimchi lalu ajak masak bersama sambil bercerita warisan Korea.
Setiap hari, saya sengaja meluangkan 15 menit mendengarkan cerita anak tanpa gangguan gadget.
Setiap interaksi penuh kasih adalah benih harapan yang tumbuh subur.
Dengan cara ini, kita memberi akar kasih yang takkan runtuh oleh teknologi apa pun.
Jangan menunggu besok—ucapkan ‘terima kasih’ pada keajaiban kecil saat anak tersenyum.
Percayalah, benih harapan itu tumbuh subur dari sentuhan manusia.
Kita tidak hanya mempersiapkan anak untuk masa depan, tapi menanam kebahagiaan yang abadi.
Source: When AI becomes an agent: Economic implications for India, Economic Times India, 2025/09/14 15:30:47
