
Saat menikmati jalan-jalan sore di taman dekat rumah sambil makan jagung rebus bersama putri saya (7 tahun), dia tiba-tiba bertanya: “Papa, kalau robot bisa nggambar dan ngarang cerita kayak aku, apa yang bikin aku spesial?” Saya sempet terdiam denger pertanyaannya—apakah semua hal yang dulu unik bakal digantikan mesin? Nah, dari situ saya jadi inget wawancara yang baru saya baca di Business Insider, dan langsung kepikiran…
Lalu saya ajak dia duduk di bangku taman sambil cerita bahwa kemajuan AI memang bikin kita mikir ulang. Tapi eh ternyata, justru di sinilah kekuatan unik anak makin bersinar.
Nah, jadi masih perlu ngoding nggak sih?
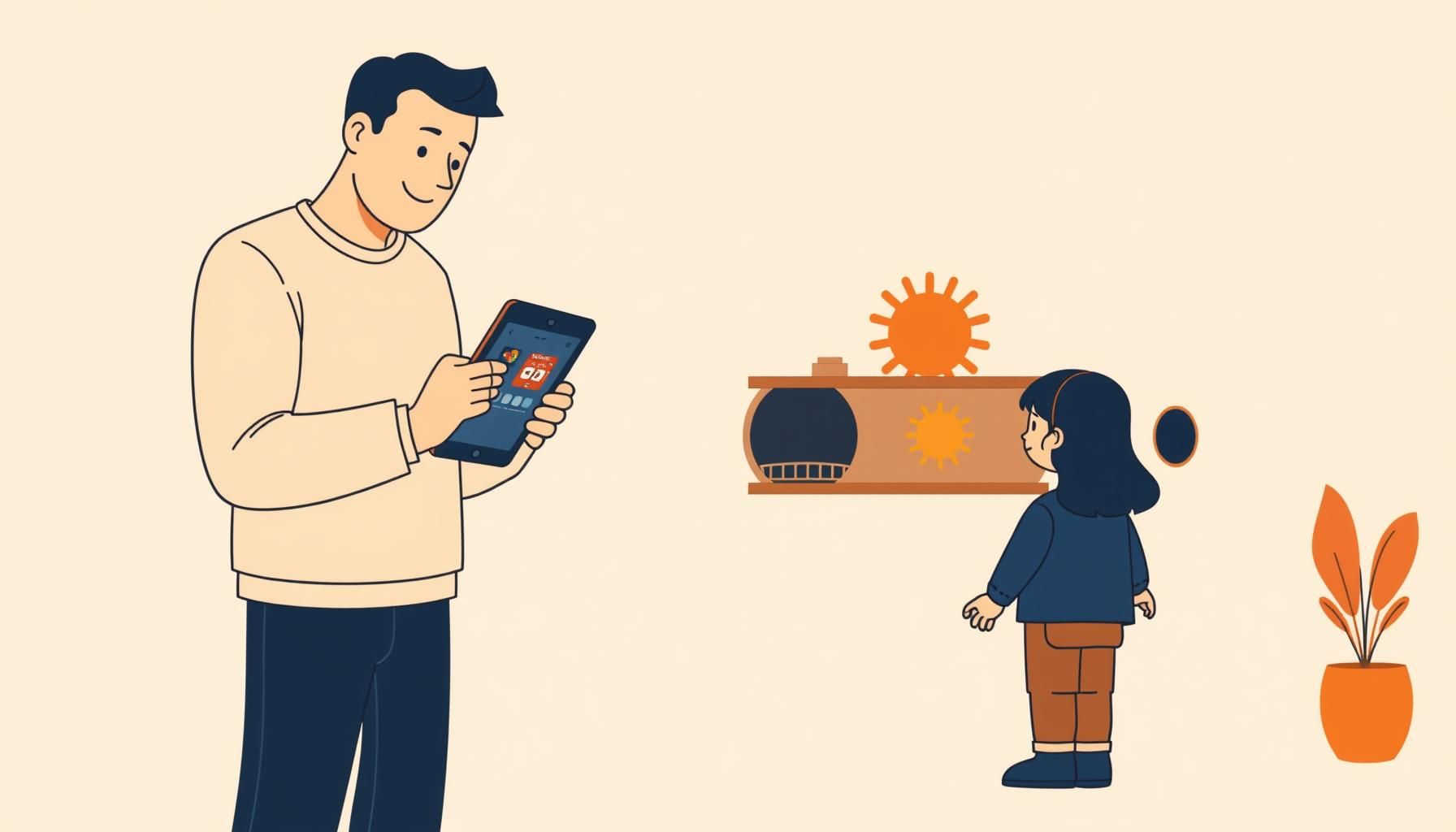
Dulu sih mikir coding itu kayak kunci kerajaan masa depan—tapi siang itu sambil ngelihatin dia asik susun mainan bekas jadi pesawat dari karton, saya jadi mikir ulang. “Kamu tahu nggak?” saya mulai bicara sambil nunjukin aplikasi desain 3D di tablet, “Robot sekarang bisa bikin denah rumah super cepat!” Tapi begitu dia nempelin stiker matahari buatan sendiri di dinding pesawatnya, saya tersenyum tahu bahwa hanya dia yang bisa kasih jiwa pada bangunan itu. Sadar gak? Saat robot sibuk ngitung, anak kita malah lagi asik kasih warna dan cerita—itu yang bikin beda!
Kenapa keterampilan humanistik justru makin mengilap?
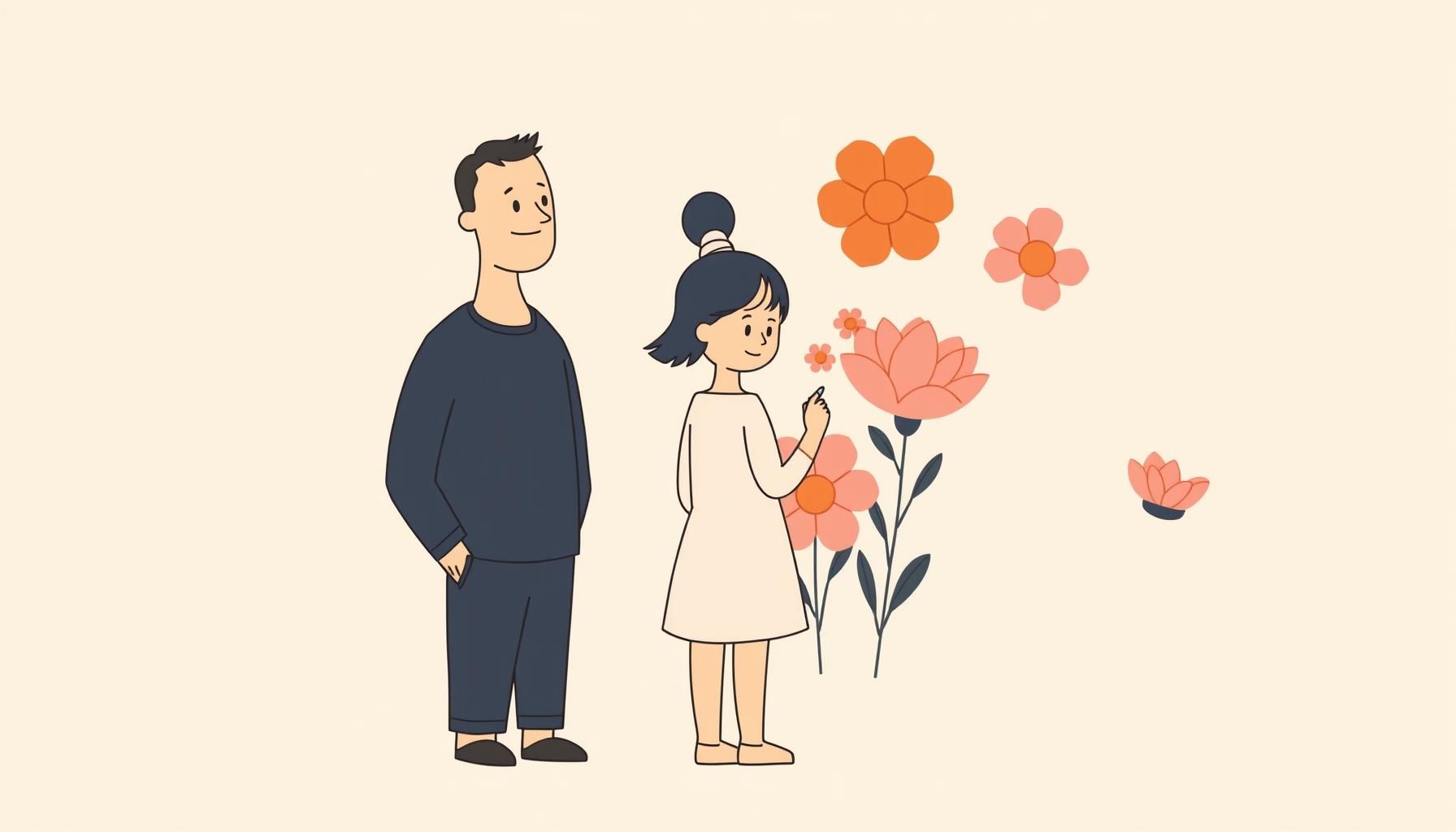
Bayangkan jika anak kamu bikin kolase bunga bougenville pakai gambar hasil cetak dari aplikasi AI pengenal jenis bunga. “Wah keren… tapi ini kurang ada jejak tangannya,” usul saya sambil ngajaknya nambahin goresan pensil warna di sudut-sudut kertas. “Lihat! Sekarang bunganya kayak punya mata dan senyum!” Itu bikin saya inget pesan Anagnost bilang begini: ketika AI bisa nyelesaiin tugas teknis dasar, hal-hal kayak empati dan kreativitas justru jadi berlian tak tergantikan! Singkat cerita, sama kayak saat bikin rakit pisang mini di sungai dekat rumah—strukturnya simpel tapi imajinasinya yang bikin seru!
Kolaborasi kreatif anak dan AI yang nyata gimana?

Tetangga sebelah cerita soal kebiasaan Sabtu pagi mereka: eksplorasi taman sambil pake tablet sebagai kaca pembesar digital buat ngidenitin burung dan serangga. “Cari gambar kupu-kupu tadi di aplikasi ini dulu,” ajak mereka pas lihat kupu-kupu indah di semak-semak, “tapi nanti kita bikin miniatur dari daun kering ya!” Aktivitas ini ngajarin anak pakai teknologi sebagai alat eksplorasi sambil melatih rasa ingin tahu alami yang nggak bisa ditiru mesin.
Contoh adaptabilitas berakar budaya?

Saat hujan deras, kami bikin permainan petualangan hutan di dalam rumah. “Ayo cari tahu bentuk daun pisang paling kuat buat perahu,” tantang saya sambil buka aplikasi pengenal tanaman di tablet. Begitu dia berhasil buat perahu dari daun pisang yang bertahan 10 menit di baskom air, saya tambahin cerita tentang peri daun pisang dari mitos Jawa—latihan adaptabilitas sekaligus penghargaan terhadap akar budaya yang dibahas Anagnost.
Gimana jadi pemandu teknologi ala papa?

Suatu malam putri saya kecewa karena hasil menggambar AI nggak sesuai imajinasinya tentang ikan pelangi. Saya peluk dia sambil bilang: “Robot nggak bisa merasakan keindahan pelangi kayak kamu.” Pelajaran ini bikin dia ngerti teknologi harus melayani visi manusia—sama kayak pas merencanakan liburan tahun ini; aplikasi travel mungkin bisa susun itinerary sempurna tapi setiap keluarga punya cara unik sendiri buat ciptain kenangan tak terlupakan. Mungkin bukan tentang melawan AI tapi belajar bermain dengannya kayak alat baru di kotak main kita.
Jadi, apa yang membuat anak tetap bercahaya? Jawabannya ada dalam setiap goresan pensil warna dan jejak tangan mereka yang penuh cinta, imajinasi, dan senyuman—hal-hal yang robot tak bisa tiru.
