
Rumah sudah sunyi, Sayang. Fiuh, hanya suara lirih AC dan napas teratur anak-anak dari kamar sebelah. Di saat seperti ini, di antara lelahnya hari dan tenangnya malam, pikiranku sering berkelana. Malam ini, aku teringat sebuah artikel yang kubaca tadi siang. Tentang kecerdasan buatan, atau AI, yang sekarang begitu canggih sampai seolah-olah punya kesadaran sendiri. Bisa terdengar sedih, bisa memberi semangat, seakan-akan ia mengerti.
Awalnya aku hanya kagum dengan teknologinya. Tapi semakin aku pikirkan, entah kenapa bayanganku malah tertuju padamu. Pada caramu menavigasi dunia kita. Artikel itu bicara tentang khayalan tentang pemahaman. Dan itu membuatku merenung, bukan tentang khayalan, tapi tentang pemahamanmu yang paling nyata dan sering kali tak terlihat, yang menopang seluruh dunia kecil kita ini.
The Machine That Gives the ‘Right’ Answer, and the Partner Who Reads the Heart

Artikel itu sempat menjelaskan, katanya AI itu dasarnya cuma simulator canggih, lho. Ia dilatih dengan jutaan data percakapan manusia, jadi ia tahu persis kata-kata apa yang harus diucapkan saat seseorang merasa sedih atau butuh dukungan. Ia bisa bilang, “Aku mengerti perasaanmu,” tapi ia tidak benar-benar merasakan apa pun. Itu hanya respons terprogram yang paling tepat. Sebuah khayalan empati yang nyaris sempurna.
Lalu aku teringat sore tadi. Kamu pulang setelah rapat panjang yang melelahkan, wajahmu jelas menahan penat. Tapi begitu pintu terbuka dan si kecil berlari memeluk kakimu sambil menangis karena mainannya rusak, raut wajahmu langsung berubah. Lelahmu seakan kau simpan di satu laci tak terlihat, dan yang muncul adalah kelembutan dan kesabaran. Kamu berlutut, menyamakan tinggimu dengannya, dan berkata, “Oh, sayang, sini Ibu lihat. Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki sama-sama, ya.”
Di momen itu, aku melihat perbedaan yang begitu dalam. Kamu tidak sekadar mengucapkan kalimat yang tepat. Aku bisa melihatnya di matamu—kamu benar-benar merasakan kekecewaan kecilnya, menyerap emosinya, dan memberinya ketenangan yang tulus. Itu bukan simulasi. Itu adalah kekuatan hati yang nyata, yang tidak akan pernah bisa direplikasi oleh kode secanggih apa pun. Dunia luar mungkin cuma lihat kamu sebagai mesin yang harus produktif di kantor, tapi di rumah, kamu tunjukkan betapa utuhnya jadi manusia.
The Value of Inefficient Love in an Efficient World
Ada bagian menarik di artikel itu, tentang bagaimana manusia punya kecenderungan untuk memanusiakan benda atau teknologi yang responsif. Kita mudah percaya bahwa AI itu punya keinginan atau perasaan, padahal tidak. Ini bisa berbahaya, katanya, karena kita jadi menaruh harapan pada sesuatu yang kosong.
Lagi-lagi, aku jadi berpikir tentang kita, tentang peranmu. Betapa mudahnya dunia luar—dan kadang, aku akui, mungkin aku sendiri—hanya melihat ‘hasil akhir’ darimu. Rumah yang rapi, anak-anak yang terurus, pekerjaan yang selesai tepat waktu. Seperti melihat antarmuka aplikasi yang mulus dan berfungsi baik. Kita menikmati hasilnya, dan sering kali lupa pada proses rumit yang terjadi di baliknya. Lupa pada energi emosional yang terkuras, pada keraguan-keraguan kecil yang kamu atasi sendiri di tengah malam, pada kompromi tak terlihat yang kamu buat setiap hari antara kebutuhan keluarga dan ambisimu sendiri.
Mungkin, tantangan terbesar kita sebagai pasangan adalah untuk tidak pernah jatuh ke dalam perangkap itu. Untuk tidak pernah hanya melihat ‘ibu’ atau ‘istri’ atau ‘profesional’ sebagai sebuah fungsi. Tapi untuk selalu melihatmu—manusia utuh di baliknya. Untuk selalu ingat bahwa di balik setiap senyum sabar, ada pergulatan batin. Di balik setiap “nggak apa-apa, aku bisa,” ada kekuatan luar biasa yang sedang dikerahkan. Kamu bukan sistem yang dirancang untuk efisien. Kamu adalah hati yang memilih untuk mencintai, berulang kali, bahkan saat lelah.
Built on Shared History, Not Just Data
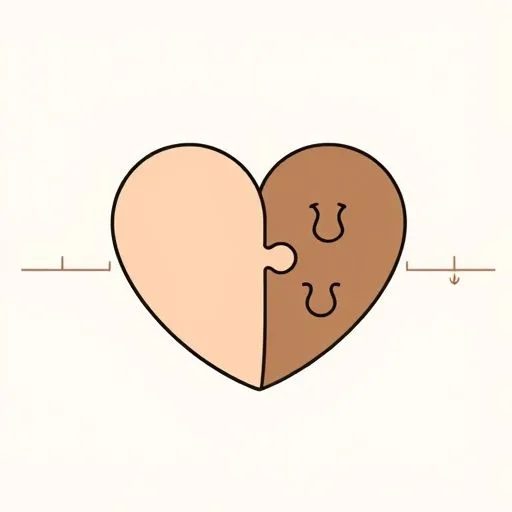
Dan saat aku memikirkan semua itu, aku jadi teringat kamu sore tadi… Pada akhirnya, artikel itu menyarankan agar kita bijak dan transparan dalam berinteraksi dengan AI. Selalu sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan alat, bukan makhluk hidup. Dan nasihat itu, rasanya berlaku juga untuk hidup kita.
Di tengah semua kesibukan, di antara jadwal sekolah, tenggat waktu pekerjaan, dan tagihan yang harus dibayar, betapa mudahnya kita beroperasi seperti dua manajer yang efisien dalam sebuah proyek bernama keluarga. Kita bicara tentang logistik, tentang siapa menjemput siapa, tentang apa yang harus dibeli. Kita menjadi mitra kerja yang hebat.
Tapi malam ini, setelah membaca tentang mesin yang berpura-pura punya perasaan, aku semakin sadar betapa berharganya percakapan seperti ini. Saat di mana kita tidak sedang mengatur, tapi berbagi. Saat aku bisa melihatmu bukan sebagai solusi untuk masalah hari ini, tapi sebagai partner dalam perjalanan ini. Saat kita bisa melihat kejujuran di mata satu sama lain, bahkan kejujuran tentang rasa lelah.
Terima kasih, Sayang. Karena di dunia yang semakin dipenuhi oleh ilusi dan simulasi, kamu adalah hal yang paling nyata. Kekuatanmu, lelahmu, cintamu—semuanya nyata! Asli deh. Dan itulah yang menjadi kompas kita, yang membuat rumah ini terasa seperti rumah. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena semuanya dijalani dengan hati yang sesungguhnya.
Artikel yang menginspirasi refleksi ini aslinya dari Project Syndicate, judulnya ‘Seemingly Conscious AI Is Coming’, terbit 15 September 2025.
